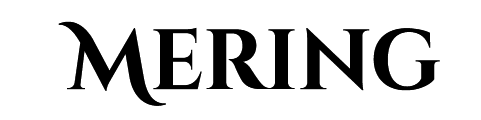|
| Penampakan buku Bapak Koperasi CU. Desain oleh Alexander Mering |
Oleh: Iram Rangi
Bayangkan seorang anak kecil di pedalaman Ketapang, Kalimantan Barat, yang tumbuh di antara sungai berliku dan hutan lebat, tanpa listrik atau buku pelajaran mewah, tapi akhirnya menjadi arsitek gerakan ekonomi yang mengubah nasib ribuan orang. Itulah Anselmus Robertus Mecer, atau yang akrab disapa Pak Mecer, sosok yang lahir dari tanah Dayak dan menjadikan keterbatasan sebagai bahan bakar perubahan.
Buku "A.R. Mecer: Bapak Koperasi Credit Union Dari Kalimantan untuk Bangsa" karya Masri Sareb Putra dan Alexander Mering bukan sekadar biografi; ia adalah manifesto hidup tentang bagaimana ekonomi kerakyatan bisa menantang hegemoni kapitalisme global. Saat saya membalik halaman pertamanya, saya seperti diajak kembali ke Pontianak tahun 1970-an, di mana semangat gotong royong masih jadi napas sehari-hari, tapi kini terancam lupa di era digital ini.
Buku setebal sekitar 230 halaman ini, diterbitkan oleh Lembaga Literasi Dayak pada Oktober 2025, menyajikan narasi yang komprehensif tentang perjalanan Mecer. Dimulai dari masa kecilnya di Kampung Menyumbung, Ketapang, di mana ia belajar bertahan hidup dari alam dan nilai-nilai adat Dayak Krio. Ayahnya, seorang petani sederhana, mengajarinya kedisiplinan melalui kerja keras di ladang, sementara ibunya menanamkan kesabaran dalam mengurus delapan anak. Buku ini menggambarkan bagaimana Mecer kecil harus berhenti sekolah tiga tahun setelah kelas tiga SD untuk membantu keluarga, tapi semangat ayahnya mendorongnya kembali belajar. Perjalanannya berlanjut ke Ketapang, tinggal di rumah keluarga Tionghoa, di mana ia pertama kali merasakan dinamika etnis dan etos kerja yang berbeda. Kemudian, ke asrama bruder di Pontianak, tempat ia belajar solidaritas di tengah diskriminasi terhadap anak-anak Dayak.
Bagian tengah buku menyoroti transformasi Mecer menjadi intelektual dan aktivis. Setelah lulus dari IKIP Bandung (kini UPI) pada 1978, ia kembali ke Kalimantan Barat sebagai dosen di Universitas Tanjungpura (Untan). Di sini, Mecer menghadapi stigma etnis: Dayak dianggap "kurang beradab" untuk posisi tinggi. Buku ini kritis menggambarkan era Orde Baru, di mana diskriminasi struktural menekan minoritas seperti Dayak, dengan kebijakan yang memprioritaskan ekstraksi sumber daya atas kesejahteraan lokal. Mecer tidak diam; ia mendirikan kelompok studi adat di FKIP Untan, mengorganisir diskusi mahasiswa, dan bahkan memasukkan sejarah Dayak ke kurikulum. Pada 1981, ia ikut mendirikan Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK), sebuah organisasi yang lahir dari kelompok diskusi informal untuk emansipasi Dayak melalui pendidikan dan ekonomi.
Puncak narasi adalah pendirian Credit Union (CU) Pancur Kasih pada 1987, dengan modal awal hanya Rp167.000. Buku ini detail menceritakan bagaimana Mecer, terinspirasi dari Friedrich Wilhelm Raiffeisen—bapak CU di Jerman—membangun sistem simpan-pinjam berbasis komunitas. Filosofi "Uang adalah Ide" menjadi inti: uang bukan sekadar kertas, tapi gagasan yang bisa diciptakan melalui kreativitas kolektif. Mecer menekankan "Empat Jalan Keselamatan"—kebutuhan konsumsi, bibit, sosial, dan rohani—sebagai fondasi CU. Buku ini juga menyertakan testimoni dari rekan seperjuangan, seperti Agustinus Tri Istanta yang mengenang semangat Mecer dalam mendampingi CU Prima Danarta, atau Amon Stefanus yang terinspirasi membaca buku atas nasihat Mecer. Bagian akhir menyajikan daftar singkatan, bibliografi, dan arsip internal, menjadikannya sumber referensi berharga.
Dibalik narasi heroik ini, buku ditulis oleh Masri Sareb Putra, seorang penulis prolifik asal Kalimantan Barat yang telah merilis ratusan buku serta memenangkan banyak penghargaan, dan Alexander Mering, seorang profesional writer, jurnalis cum sastrawan yang telah banyak menulis karya sastra serta biografi tokoh penting di Indonesia, antar alain Teddy Kardin & Nyoman Nuarta.
Secara kritis, buku ini kuat dalam menyoroti bagaimana CU menjadi resistensi kultural terhadap marginalisasi Dayak. Ia mengkritik tajam kebijakan Orde Baru yang merampas hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH), meninggalkan masyarakat lokal dalam kemiskinan. Mecer digambarkan sebagai pembebas, mengubah "orang kita" dari objek menjadi subjek ekonomi. Namun, ada kelemahan: narasi terkadang terlalu heroik, kurang mendalami kegagalan atau konflik internal dalam gerakan CU, seperti tantangan skalabilitas di era digital atau kompetisi dengan fintech modern. Buku ini juga bisa lebih kritis terhadap konteks nasional, misalnya bagaimana Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan sering jadi jargon kosong, sementara CU seperti Pancur Kasih berhasil karena akar lokalnya.
Melihat ke depan, buku ini memicu renungan filosofis tentang masa depan ekonomi Indonesia. Di tengah dominasi kapitalisme pasar bebas, di mana korporasi raksasa menguasai sumber daya, gagasan Mecer mengingatkan kita pada esensi gotong royong.
Bayangkan jika model CU diterapkan lebih luas: bukan sekadar simpan-pinjam, tapi ekosistem yang mengintegrasikan teknologi seperti blockchain untuk transparansi, sambil mempertahankan nilai solidaritas. Seharusnya pemerintah melihat ini sebagai peluang, dengan mengintegrasikan CU ke dalam kurikulum pendidikan nasional, bukan hanya di perguruan tinggi tapi sejak sekolah dasar, agar generasi muda belajar bahwa kekayaan sejati lahir dari ide kolektif, bukan akumulasi individu.
Filosofisnya, seperti kata Mecer, "uang adalah ide"—mirip pemikiran Aristotle tentang eudaimonia, di mana kesejahteraan bukan dari harta, tapi harmoni sosial. Di Indonesia yang beragam, CU bisa jadi jembatan antar-etnis, mencegah konflik seperti di Papua atau Maluku. Tapi tanpa komitmen politik, ia berisiko tersisih oleh narasi "ekonomi instan" ala startup global. Buku ini mengajak kita bertanya: apakah kita mau kembali ke akar kerakyatan, atau terus biarkan pasar bebas menggerus identitas bangsa?
Pada akhirnya, buku yang diterbitkan oleh Lembaga Literasi Dayak ini bukan hanya tentang Mecer, tapi tentang kita semua. Dari kota kelahiran penulis (Pontianak yang panas dan ramai), saya melihatnya sebagai panggilan untuk bertindak. Baca buku ini, dan Anda akan merasa seperti Mecer kecil di hutan: penuh hambatan, tapi juga peluang tak terbatas. Di era ketidakpastian ini, jejak Mecer mengingatkan bahwa perubahan dimulai dari satu ide sederhana—dan itu bisa dari siapa saja, termasuk Anda, para pembaca yang budiman.