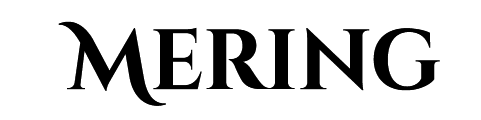|
| Cover buku Cerpen Jaya Ramba karya graphic designe Alexander Mering. Sumber Foto: Borneo Globe |
Oleh: Iram Rangi
KUCHING-Kau bisa menulis dengan tinta, tetapi Jaya Ramba
menulis dengan darah.
Darah warisan, darah luka, darah yang mengalir dari sejarah panjang suku Dayak
yang pernah dianggap sunyi. Kumpulan cerpennya, Upacarakan Aku Dengan Darah
Keturunan, bukan sekadar buku sastra—ia adalah upacara kesadaran. Setiap
halamannya berdenting seperti gong tua yang dibangunkan dari tidur panjang,
memanggil roh-roh leluhur agar duduk sebentar di antara kata dan makna.
Dalam dunia sastra yang kian sibuk dengan gaya, formula, dan
algoritma pasar, Jaya Ramba muncul seperti seorang dukun yang datang membawa
kitab kuno. Ia tidak menulis untuk memanjakan pembaca, tapi untuk menguji
apakah pembaca masih sanggup menatap api roh yang tidak bisa dimatikan. Di
tangan Jaya, kata menjadi mantra, cerita menjadi ritual, dan membaca menjadi
pengalaman spiritual yang tidak bisa dilakukan dengan pikiran dingin.
Karya Jaya bukan nostalgia etnik murahan. Ia bukan turis
dalam kebudayaannya sendiri. Ia berdiri di tengah hutan identitas yang terus
digunduli modernitas, dan dari sana ia menulis ulang sejarah bangsanya.
Ritual, sabak, bebiau, hingga upacara penyembuhan bukan sekadar ornamen
eksotik—itu sistem pengetahuan. Ia mengajarkan bahwa roh dan manusia tak bisa
dipisahkan seperti daging dari tulang.
Ceritanya dipenuhi watak “aku” yang bisa jadi siapa saja:
penyaksi, pewaris, bomoh, atau roh gentayangan yang menolak dilupakan. Ia
berbicara dengan sungai, menatap tanah sebagai rahim ingatan, dan membiarkan
api berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal di kota. Inilah bentuk realisme
sakral—sebuah gaya yang mempersatukan dunia nyata dengan dunia roh tanpa
menuntut pembaca untuk memilih salah satu.
Yang menarik, Jaya Ramba menulis seolah-olah seluruh semesta
ikut duduk di meja tulisnya.
Sungai bukan sekadar latar, melainkan saksi sumpah. Hutan bukan dekorasi hijau,
tapi nadi peradaban. Dalam setiap cerpen, ada keseimbangan antara pengorbanan
dan kebangkitan, antara roh dan daging, antara kematian dan kelahiran. Ia
menulis bukan untuk melarikan diri dari dunia modern, tetapi untuk mengingatkan
bahwa dunia modern sedang kehilangan jiwanya.
Sebagian kritikus menyandingkannya dengan Gabriel García Márquez, Chinua Achebe, dan Pramoedya Ananta Toer. Tapi perbandingan itu hanya setengah benar.
Karena Ramba tidak meniru siapa pun—ia menulis dengan logika hutan dan napas
arwah. Ia meminjam ritme mantra, melagukan narasi dengan tempo gong, dan
menutup kalimatnya seperti menutup peti persembahan.
Karya-karyanya tidak hanya penting bagi kesusastraan Dayak,
tapi juga bagi seluruh wacana sastra dunia yang kini mulai menoleh pada
“indigenous literature”—sastra pribumi yang menulis dari pinggir, bukan dari
pusat kekuasaan.
Ia adalah suara dari akar yang tumbuh ke atas, bukan daun yang jatuh ke bawah.
Bagi dunia akademik, karya ini adalah bahan penelitian yang
kaya. Bagi pembaca, ini adalah perjalanan ziarah. Dan bagi masyarakat Dayak,
ini adalah cara roh mereka diabadikan di antara halaman.
Tidak heran jika Upacarakan Aku Dengan Darah Keturunan kini disebut
sebagai teks peralihan—dari sastra etnik menuju sastra dunia. Sebuah karya yang
menolak tunduk pada ekspektasi pasar, tapi justru memaksa pasar tunduk pada
kesakralan budaya.
Ramba telah membuktikan bahwa bahasa bisa menjadi altar, dan
menulis adalah bentuk persembahan. Ia bukan sekadar penulis, tapi penjaga api
pengetahuan yang hampir padam.
Di tangan lain, sastra menjadi hiburan. Di tangannya, sastra menjadi upacara.
Kini, Jaya Ramba berdiri di ambang sejarah sastra Asia
Tenggara. Ia menulis dari Borneo, tapi gema suaranya sampai ke ruang seminar,
ruang universitas, dan ruang batin siapa pun yang pernah merasa tercerabut dari
asal. Ia tidak menulis untuk menjadi terkenal, tapi untuk menyembuhkan kehilangan
kolektif yang diwariskan oleh kolonialisme dan modernitas.
Dan di situlah letak kekuatannya: ia tidak menjual
eksotisme, tetapi menawarkan kesadaran.
Sastra, baginya, bukan sekadar estetika—tapi cara memulihkan dunia yang telah
melupakan makna roh.
Setiap kali kita membuka halaman bukunya, kita seperti
sedang menghadiri upacara.
Ada mantra yang disembunyikan di antara dialog, ada roh yang bersembunyi di
balik kalimat, dan ada darah keturunan yang masih hangat di setiap kata.
Membaca Jaya Ramba adalah seperti melihat parang tua yang berkarat, tapi setiap
goresannya menceritakan sejarah bangsa yang bertahan.
“Upacarakan Aku Dengan Darah Keturunan” bukan sekadar
kumpulan cerpen. Ia adalah pernyataan: bahwa dari suku kecil bisa lahir gagasan
besar, bahwa dari akar bisa tumbuh pohon yang menjulang menembus langit sastra
dunia.
Dan dunia kini tidak punya pilihan lain selain mengakuinya:
pena Dayak telah menulis sejarahnya sendiri—dengan darah yang tidak bisa
dikeringkan.