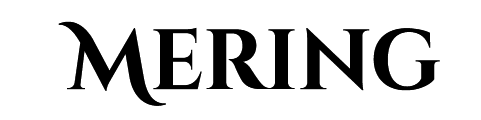|
| Damianus Syiok, sang Penulis memamerkan buku Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak. Dok penulis |
Oleh: Iram Rangi
Apakah Anda pernah berpikir, mungkinkah di aorta dan nadi yang berdenyut di tubuh Anda, masih mengalir darah seorang budak? Atau darah seorang bangsawan yang pernah memerintah ribuan jiwa di pedalaman Borneo? Pertanyaan itu, seperti cambuk halus yang menghantam kesadaran, menjadi pintu masuk untuk membaca buku Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak – Latar Belakang Pertemuan Tumbang Anoi 1894. Sebuah karya yang menyingkap lapisan sejarah yang kerap ditutup debu mitos dan kabut romantisme etnik.
Buku ini tidak sedang bercerita tentang heroisme Dayak
semata, tapi tentang luka dan kegetiran yang membentuk fondasi moral
masyarakatnya. Ia adalah catatan panjang tentang bagaimana manusia bisa saling
memperbudak, saling mengayau, dan akhirnya saling memaafkan dalam satu
pertemuan sakral bernama Tumbang Anoi 1894—peristiwa monumental yang
mengubah wajah peradaban Borneo dari zaman kepala terpenggal ke zaman kepala bermusyawarah.
Tentusaja penulis tidak menulis sejarah sebagai fosil, tapi
sebagai darah yang masih hangat mengalir. Ia membawa kita menyelam dalam dua
dunia: budaya Kuta dan betang lama—zaman di mana perang, perbudakan, dan
pengayauan menjadi hukum hidup; dan budaya betang Dayak yang baru. Zaman
yang lahir dari keberanian untuk mengakhiri semua pengalaman pahit itu. Seperti
metamorfosis, Dayak berubah bukan karena paksaan kolonial, tapi karena
kesadaran diri: bahwa manusia bukan hanya makhluk yang bisa bertahan, tetapi
juga bisa bertumbuh.
Dalam budaya betang lama, hidup adalah hierarki
tajam. Ada bangsawan, orang merdeka, dan ada budak—makhluk tanpa hak, yang
nilainya bahkan kalah dari seekor kerbau. Catatan Schwaner dan Tromp
menyebutkan, di beberapa daerah, harga seorang budak setara dengan seekor babi.
Bayangkan, manusia dijual seperti daging di pasar adat. Anak-anak budak bisa
dipisahkan dari orang tuanya, diperdagangkan, atau dikurbankan dalam upacara
adat karena lebih “ekonomis”. Pembaca modern mungkin tercekat, tapi inilah
realitas sosial yang ditulis jujur tanpa glorifikasi.
Penulis berhasil menghidupkan kembali suara-suara dan drama berdarah
itu. Dalam catatan lama disebutkan, perang antara orang Barito melawan
Kapuas–Kahayan–Katingan berlangsung berbulan-bulan, bahkan memakai artileri dan
senjata api. Tubuh-tubuh bergelimpangan, dan lelaki dewasa menjadi populasi
yang langka. Dari sini, kita memahami betapa mahal harga perdamaian itu—karena
ia dibayar dengan generasi yang hilang.
Namun, yang paling menarik dari buku ini bukan hanya detail
sejarahnya, melainkan pesan moral yang menembus waktu: Dayak dulu bukanlah
“biadab” seperti yang ditulis kolonial, melainkan masyarakat yang hidup di
dalam sistem nilai yang keras, dan perlahan menemukan jalan keluar dari
kekerasan itu sendiri. Itulah makna sejati dari Pertemuan Tumbang Anoi 1894—bukan
sekadar peristiwa adat, melainkan titik lahirnya kesadaran kolektif bahwa
kemanusiaan lebih tinggi dari dendam.
Selama tiga bulan para kepala suku berkumpul, berdialog, dan
berikrar: tidak ada lagi perang, tidak ada lagi perbudakan. Mereka menanggalkan
pedang, memutus rantai, dan membuka pintu bagi dunia luar. Dari pertemuan
itulah lahir budaya betang baru—sebuah masyarakat yang mulai menghargai
ilmu pengetahuan, membuka diri pada pendidikan, dan menolak balas dendam
sebagai jalan hidup. Inilah babak baru Borneo, yang kemudian ikut membangun
peradaban bersama Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Buku ini memadukan disiplin riset dengan keindahan narasi.
Sumber-sumber klasik seperti Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van
Nederlandsch-Indië (1861) dan tulisan para pelancong Eropa digunakan dengan
presisi, tapi tidak membuatnya terasa akademis kering. Penulis menulis seperti
seorang pendongeng tua di tepi sungai Kahayan—tenang, dalam, tapi menyimpan
bara pengetahuan. Pada edisi ketiga dan keempat, sistem sitasi pun diperbarui
menjadi gaya Chicago, seolah menunjukkan bahwa sejarah Dayak kini bisa berdiri
setara dengan sejarah bangsa mana pun, tanpa perlu lagi bersandar pada cara
berpikir kolonial.
Membaca buku ini membuat kita bertanya ulang tentang
asal-usul. Apakah kakek buyut kita dulu seorang tuan yang memiliki kuta megah
dari kayu ulin, atau justru seorang budak yang tinggal di bilik sempit, menanak
nasi untuk majikannya? Pertanyaan seperti itu bukan untuk menimbulkan rasa malu,
tapi rasa ingin tahu tentang akar kemanusiaan kita sendiri.
Rosadi Jamani pasti akan tersenyum membaca buku semacam ini.
Karena di sinilah sejarah bekerja seperti cermin: ia memperlihatkan wajah masa
lalu agar kita bisa memperbaiki wajah masa depan.
Dan bagi mereka yang ingin tahu lebih jauh—atau mungkin
diam-diam ingin menelusuri darah leluhurnya di antara kisah para budak dan
bangsawan Dayak—buku ini bisa didapatkan lewat agen resmi: anyarmart.com.
Sejarah, bagaimanapun, bukan milik pemenang atau pecundang. Ia milik mereka yang berani membaca dan tidak takut menemukan dirinya di dalamnya.