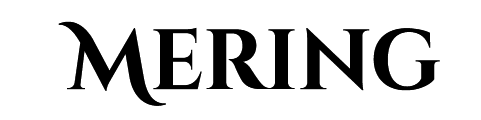|
| Buku The History of Dayak. Design by Alexander Mering |
Oleh: Iram Rangi
Di tengah derasnya arus globalisasi dan reduksi budaya yang
terjadi di seluruh penjuru dunia, muncul sebuah buku yang menolak dilupakan. The
History of Dayak – Penghuni Asli Varuna-dvipa (Borneo) bukan sekadar karya
sejarah; ia adalah pernyataan eksistensial sebuah bangsa yang selama
berabad-abad hanya menjadi objek tulisan orang lain.
Buku setebal sekitar lima ratus halaman ini ditulis oleh dua
nama yang tak asing dalam ranah kajian kebudayaan Borneo: Prof. Tiwi Etika,
Ph.D., dan R. Masri Sareb Putra, M.A.. Keduanya datang bukan dari
menara gading akademik luar, tetapi dari akar tanah itu sendiri—orang Dayak
yang menulis sejarah Dayak. Disunting dan diberi sentuhan desain visual oleh AlexanderMering, yang juga merancang sampul buku ini dengan kepekaan artistik
yang halus, buku ini menampilkan harmoni antara akademik dan estetika. Edisi
terbitan Lembaga Literasi Dayak ini diedarkan secara eksklusif oleh anyarmart.com,
seolah menegaskan bahwa literasi Dayak kini berdiri di rumahnya sendiri.
Dalam pengantar yang ditulis Prof. Dr. Rizali Hadi,
seorang akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, pembaca segera dibawa ke
inti moral buku ini: sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan peristiwa,
melainkan residu makna yang menunggu ditafsirkan. Rizali menulis dengan nada
puitis, nyaris seperti prolog sebuah novel: “Ketika leluhur di Gua Niah
menyalakan api di gelap malam prasejarah, garis hidup itu terus berdenyut
hingga hari ini.” Kalimat semacam itu segera memberi tahu kita bahwa buku ini
bukan sejarah yang dingin, melainkan kisah yang bernapas.
Membalik Narasi Kolonial
Buku ini berdiri di atas tesis berani: bahwa orang Dayak
bukan pendatang, bukan hasil migrasi dari daratan Asia, tetapi penghuni asli
Pulau Borneo sejak 40.000 tahun lalu. Para penulis membangun argumen itu
melalui pendekatan multidisipliner—arkeologi, linguistik, genetika, hingga
filsafat budaya. Mereka mengutip riset Tom Harrisson di Gua Niah,
analisis linguistik Robert Blust, serta teori kontinuitas Peter
Bellwood, lalu memadukannya dengan tradisi lisan Dayak yang diwariskan
turun-temurun.
Di tangan penulis yang lain, kombinasi sains dan mitos
mungkin terasa canggung. Namun di tangan Etika dan Sareb Putra, keduanya
melebur menjadi narasi yang meyakinkan. Mereka menulis seperti antropolog yang
mencintai subjeknya tanpa kehilangan jarak ilmiah. “Dayak bukan sekadar
penghuni hutan,” tulis mereka, “melainkan penjaga kosmos ekologis Borneo.”
Kalimat itu menggema lama, terutama ketika dunia hari ini kian kehilangan
keseimbangan ekologis yang dulu pernah dijaga dengan ritual dan kearifan.
Arkeologi Sebagai Puisi
Salah satu kekuatan buku ini adalah kemampuannya mengubah
bahasa akademik menjadi pengalaman puitis. Bab-bab awal, yang membahas Deep
Skull dari Gua Niah, lukisan cadas kuno, dan jejak linguistik Austronesia,
dibingkai dengan semangat penemuan diri. Para penulis seolah menggali fosil
bukan hanya dari tanah, tetapi juga dari kesadaran kolektif orang Dayak.
Namun yang paling menonjol bukan sekadar data atau teori,
melainkan nada batin yang mengalir di antara paragraf. Ada kelembutan sekaligus
keyakinan di sana—nada yang lahir dari rasa memiliki. Ketika mereka menulis
bahwa “historiografi Dayak adalah medan kuasa,” kita tahu bahwa ini bukan
sekadar analisis Foucauldian, melainkan pernyataan pengalaman. Dayak tidak lagi
mau dilihat dari luar; mereka menulis dari dalam, menulis dirinya sendiri.
Struktur yang Menyatu antara Fakta dan Jiwa
Buku ini terbagi ke dalam lima bagian besar yang berjalan
seperti aliran sungai: dari prasejarah, kolonialisme, perlawanan, kebangkitan
ekonomi, hingga literasi modern. Setiap bagian menampilkan struktur naratif
yang cermat namun tidak kaku. Penulis menggunakan bahasa yang mengalir,
menghindari jargon yang memisahkan akademisi dari pembaca umum.
Bab “Dayak Dijajah ‘Hanya’ 50 Tahun” misalnya, mengandung
nada ironis yang segar—menggugah pembaca untuk memikirkan ulang makna
penjajahan. Di bab lain, kisah lahirnya Credit Union Pancur Kasih
disajikan bukan sebagai data ekonomi, melainkan sebagai kisah keberanian moral
dan solidaritas komunitas. Sejarah di sini bukan catatan masa lalu, tetapi peta
arah masa depan.
Sampul dan Visual: Simbolisme yang Tenang
Desain sampul oleh Alexander Mering pantas mendapat pujian tersendiri. Tak hanya bertindak sebagai editor, Mering yang juga memang memiliki talenta dalam seni lukis dan visual grafis kali ini memilih salah satu karya ilustrasinya yang bergaya scratchboard art monokrom yang menampilkan sosok pria Dayak dalam balutan atribut adat, digores dengan ribuan garis halus yang membangun kesan kekuatan, keheningan, dan keagungan spiritual Borneo. Figur lelaki Dayak itu berpadu dengan garis-garis abu-abu memanjang tak hanya membentuk lekuk background hitam di belakangnnya tetapi juga sebuah metafora tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur yang menghidupi tanah Kalimantan. Perpaduan warna hitam pekat dan kelabu memberi kesan mistis sekaligus misterius, seolah kita sedang menggenggam rahasia Borneo yang selama ini belum seluruhnya terungkap. Ini bukan sekadar desain; ini pernyataan identitas visual yang sejajar dengan isi buku.
Sebuah Buku dengan Dua Jiwa
Membaca The History of Dayak terasa seperti
menelusuri dua arus sekaligus: satu ilmiah, satu spiritual. Di satu sisi, buku
ini disusun dengan ketelitian data yang layak untuk ruang kuliah sejarah. Di
sisi lain, ia memiliki irama seperti doa panjang tentang rumah dan asal-usul.
Di antara halaman-halaman yang padat, sesekali muncul
perenungan filosofis yang nyaris mistik. Seperti ketika mereka menulis, “Mengenal
Dayak sesungguhnya adalah mengenal manusia dalam kedalaman dirinya.” Kalimat
itu menggemakan semboyan Yunani kuno gnōthi seauton—kenalilah
dirimu—yang juga menjadi inspirasi pembuka dalam prakata.
Refleksi dan Relevansi
Mungkin inilah nilai paling berharga dari buku ini: ia tidak
berhenti pada nostalgia masa lalu. Para penulis menautkan sejarah Dayak dengan
persoalan masa kini—perubahan iklim, migrasi, dan pemindahan ibu kota negara
(IKN). Dengan cara itu, The History of Dayak menjelma menjadi jembatan
antara mitos dan modernitas.
Bagi pembaca luar Borneo, buku ini membuka jendela baru
tentang makna “masyarakat adat”. Bukan sebagai kategori etnografis yang
eksotik, tetapi sebagai simbol kebijaksanaan ekologis dan ketahanan moral. Di
tengah dunia yang mengukur kemajuan dengan beton dan angka, Dayak dalam buku
ini menawarkan alternatif: kemajuan yang berakar pada harmoni dan kearifan.
Sejarah yang Kembali Bernapas
Sebagai karya sejarah, buku ini menegakkan standar baru. Ia
tidak hanya menulis ulang narasi kolonial, tetapi juga menulis ulang cara kita
memahami sejarah itu sendiri. The History of Dayak mengingatkan bahwa
setiap bangsa berhak memiliki arsipnya sendiri—bahkan jika arsip itu disimpan
dalam nyanyian, ritual, atau ingatan hutan.
Dalam panorama literatur Indonesia modern, buku ini berdiri
sebagai monumen kecil yang bersinar dari pedalaman Borneo. Ia menyatukan ilmu
dan cinta tanah; sains dan spiritualitas; teks dan akar.
Dan mungkin, sebagaimana ditulis oleh Rizali Hadi dalam pengantarnya yang penuh
keyakinan, “Kebesaran sejati sebuah peradaban adalah ketika ia mampu menulis
dirinya sendiri.”
The History of Dayak – Penghuni Asli Varuna-dvipa (Borneo)
Penulis: Prof. Tiwi Etika, Ph.D. & R. Masri Sareb Putra, M.A.Pengantar: Prof. Dr. Rizali Hadi
Editor & Desainer Sampul: Alexander Mering, S.H.
Penerbit: Lembaga Literasi Dayak
Distributor resmi: anyarmart.com
Jakarta, Oktober 2025