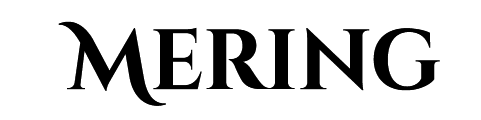Di tengah semarak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang
terus bergulir dengan deru mesin dan geliat pembangunan infrastruktur,
Kalimantan Timur tak hanya sibuk mengangkat crane dan menggali fondasi beton.
Ada pula kerja-kerja sunyi namun penting yang sedang berlangsung: menjaga
keamanan sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal. Dua agenda ini
kini jadi sorotan utama di tengah akselerasi transformasi wilayah menjadi
episentrum pemerintahan baru Indonesia.
Salah satu upaya konkret datang dari DPRD Kalimantan Timur yang kini mempercepat proses pemetaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tersebar di wilayah tersebut. Dalam suasana politik dan ekonomi yang mulai menggeliat seiring dengan pemindahan pusat kekuasaan nasional ke IKN, DPRD menyadari bahwa stabilitas sosial adalah kunci yang tak bisa ditawar. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, dalam pernyataannya menekankan bahwa keberadaan ormas tak bisa dipandang sebelah mata. Di satu sisi, ormas adalah motor penggerak masyarakat sipil yang bisa berkontribusi dalam pembangunan; namun di sisi lain, tak sedikit kasus menunjukkan ormas dapat menjadi sumber gangguan jika tidak dikelola dengan baik.
“Keamanan adalah kunci utama dalam mendukung iklim investasi yang sehat. Kita tidak boleh lengah, karena situasi yang tidak stabil akan menimbulkan keraguan, baik dari masyarakat maupun calon investor,” ujar Sapto lugas, menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem sosial yang kondusif di tengah mega-proyek IKN yang menjadi sorotan nasional dan internasional.
Lebih dari sekadar teori, kekhawatiran itu nyatanya berakar dari realitas. DPRD Kaltim menerima sejumlah laporan mengenai adanya oknum ormas yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penambangan tanpa izin hingga praktik pungutan liar. Aktivitas ini bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pembangunan. Maka dari itu, DPRD menegaskan bahwa pemetaan ormas bukan sekadar proses inventarisasi, tetapi lebih jauh lagi—sebuah proses evaluasi mendalam. Mana ormas yang benar-benar aktif dalam memberdayakan masyarakat? Dan mana yang justru menjadi parasit yang menghambat kemajuan?
Sapto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Menurutnya, pemetaan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan: kepolisian, kejaksaan, hingga forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). “Kita harus tahu siapa yang berkontribusi positif dan siapa yang justru menjadi sumber keresahan. Pemetaan ini harus komprehensif,” tegasnya.
Tak hanya berhenti pada tahap identifikasi, langkah tegas juga menjadi sorotan. Ormas yang terbukti terlibat dalam kejahatan seperti menjadi backing tambang ilegal atau pelaku pungli akan ditindak tanpa toleransi. Penegakan hukum harus berlaku tanpa pandang bulu. Hal ini menjadi bagian dari komitmen bersama menjaga ketertiban dan menciptakan ruang yang sehat untuk investasi dan kehidupan masyarakat. Sapto menegaskan, “Tidak ada toleransi bagi ormas yang terlibat praktik melawan hukum. Ini bagian dari komitmen kita menjaga ketertiban dan menciptakan ruang yang kondusif bagi investasi, apalagi Kaltim kini menjadi sorotan nasional sebagai pusat pemerintahan baru.”
Langkah ini secara tidak langsung menjadi perisai pelindung IKN dari potensi disrupsi sosial yang kerap muncul di tengah transformasi masif seperti ini. Pemetaan ormas menjadi strategi pencegahan dini, agar ketika IKN nanti berdiri sepenuhnya sebagai ibu kota negara, tidak ada bara api sosial yang mengendap dan tiba-tiba menyala.
Sementara di sisi lain Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)—wilayah yang akan menjadi jantung dari IKN—juga tak tinggal diam dalam menghadapi tantangan pergeseran zaman. Mereka sadar bahwa pembangunan bukan hanya soal beton, gedung tinggi, atau jalur transportasi canggih. Pembangunan sejati adalah ketika manusia lokal mampu mengambil peran sentral, menjadi subjek, bukan objek dari perubahan. Maka dari itu, pada awal Juli 2025, rombongan dari Pemkab PPU melakukan kunjungan kerja ke Kota Yogyakarta, sebuah kota yang dianggap berhasil merawat budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
Dipimpin oleh Wakil Bupati Abdul Waris Muin, rombongan tersebut disambut hangat oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Nakula, Balai Kota Yogyakarta, kedua belah pihak terlibat dalam dialog strategis yang jauh dari sekadar seremoni. Ini adalah pertemuan dua wilayah yang berada dalam orbit berbeda—satu di tengah transformasi modern sebagai ibu kota baru, dan satu lagi yang telah lama dikenal sebagai pusat kebudayaan dengan denyut ekonomi kreatif yang konsisten.
“Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang sukses dalam pengembangan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Kami ingin belajar dari strategi serta langkah-langkah konkret yang telah dilakukan, agar dapat diadaptasi di PPU,” ucap Abdul Waris dengan antusias.
Bagi Pemda PPU, ini bukan sekadar studi banding biasa. Mereka tengah mencari inspirasi nyata yang bisa disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Kalimantan Timur. Fokus mereka adalah pada bagaimana mengelola potensi daerah dengan tetap memelihara kearifan lokal, bagaimana warga bisa dilibatkan secara aktif dalam pembangunan, dan bagaimana kebijakan bisa membumi tanpa kehilangan esensi budaya.
Wawan Hermawan pun berbagi cerita yang sangat relevan. Kota Yogyakarta yang minim sumber daya alam nyatanya mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh. “Kami ini sebenarnya kepepet,” aku Wawan, “karena tidak punya sumber daya alam. Tapi justru dari situ kami dituntut untuk menjadi kreatif.”
Salah satu contoh konkret adalah revitalisasi Batik Segoro Amarto Reborn, sebuah program pelestarian batik klasik yang sepenuhnya dikerjakan secara manual—tanpa teknik printing. Dalam program ini, pelajar dan pegawai daerah dilibatkan melalui pembentukan koperasi yang dinamai Koperasi Merah Putih. Prinsip nasionalisme dan ekonomi rakyat menjadi dasar dari inisiatif ini. “Kami secara tegas melarang teknik printing dalam produksinya, demi menjaga keaslian dan memberdayakan perajin batik lokal,” jelas Wawan.
Model seperti ini sangat mungkin untuk direplikasi di PPU. Dengan banyaknya komunitas adat dan kekayaan budaya lokal yang belum tergarap maksimal, pendekatan semacam ini bisa menjadi landasan pembangunan ekonomi berbasis budaya. Apalagi dalam konteks IKN, yang dari awal sudah diposisikan sebagai ibu kota negara yang ramah lingkungan dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal, langkah semacam ini menjadi sangat relevan.
Kunjungan ke Yogyakarta ini sekaligus menegaskan bahwa PPU tidak sekadar menjadi pelengkap dalam pembangunan IKN. Mereka ingin menjadi bagian aktif, bahkan sentral dalam menyusun strategi pembangunan yang tangguh dan inklusif. Menurut Pemda PPU, kerja sama antardaerah harus dibangun sebagai fondasi jaringan ekonomi yang lebih luas, sehingga pembangunan IKN tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat, tapi juga mengakar ke rakyat di daerah-daerah penyangga.
Dalam konteks besar pembangunan IKN, dua upaya ini—pemetaan ormas untuk menjaga stabilitas, dan penyerapan ilmu dari Yogyakarta untuk memperkuat basis ekonomi lokal—adalah dua sisi dari koin yang sama. Satu menjaga ketertiban agar perubahan bisa berlangsung damai, dan satu lagi memastikan bahwa masyarakat lokal tidak tertinggal dalam proses transformasi ini.
Dan di sanalah titik temu keduanya: menjaga ketertiban dan memberdayakan masyarakat. Karena IKN, pada akhirnya, bukan hanya proyek arsitektural atau tata kota, melainkan juga proyek sosial jangka panjang—tentang bagaimana bangsa ini mengelola dirinya sendiri dalam wajah yang baru.