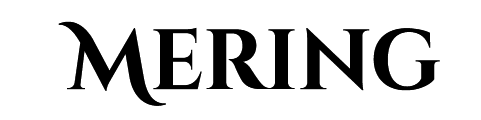Kuching, Sarawak – Bayangkan Anda sedang duduk di tepian sungai yang tenang. Heningnya air hanya diselingi desir semilir angin—lalu tiba-tiba sebuah sirip gelap muncul, perlahan menyelinap ke tepi. Momen itu adalah mimpi buruk yang sudah menjadi kenyataan bagi beberapa komunitas di Sarawak. Serangan buaya yang mematikan bukan lagi kisah rakyat tua, melainkan ancaman nyata. Kini, dengan populasi reptil ini makin menggila, pemerintah Sarawak mengambil langkah drastis: mengirim tim ke Australia guna mempelajari sistem pengelolaan buaya dunia maju. Apakah model itu akan menyelesaikan krisis atau sekadar menjadi eksperimen mahal?
Sejak dekade 1980-an, populasi buaya muara (Crocodylus
porosus) Sarawak mengalami penurunan dramatis akibat perburuan, degradasi
habitat, dan gangguan sungai oleh aktivitas manusia. Namun dalam puluhan tahun
terakhir, upaya perlindungan dan regulasi telah membalik tren. Kini,
diperkirakan terdapat sekitar 25.000 individu buaya tersebar di lebih dari 40
DAS (daerah aliran sungai) di Sarawak (Sarawak Tribune, 2025). Angka ini hampir
dua kali lipat dibandingkan jumlah tercatat sekitar 13.500 pada tahun 2014 (The
Borneo Post, 2025).
Kecenderungan ini turut tercermin dalam studi lokal. Di DAS
Samarahan, misalnya, survei malam menggunakan metode “spotting” mencatat 1.022
buaya antara 2019 dan 2021 di tiga sungai terpilih (Belat, Tuang, Sabang)
(Hassan et al., 2023). Kepadatan relatif buaya naik dari sekitar 0,98 individu
per km (2019) menjadi 6,49 individu per km (2021) (Hassan et al., 2023). Ini
menandakan lonjakan populasi yang tak bisa lagi dianggap enteng.
Kenaikan jumlah buaya berbanding lurus dengan peningkatan
konflik manusia–buaya (HCC – Human Crocodile Conflict). Menurut laporan ilmiah
terkini, pemulihan populasi C. porosus memang berhasil, tetapi insiden HCC juga
jadi lebih sering (Samuel et al., 2025). Konflik ini bisa berupa luka serius,
hilangnya jiwa, atau kerugian ekonomi bagi masyarakat di pesisir sungai.
Menjajal Model Australia: Apa yang Bisa Dipelajari?
Premier Sarawak, Abang Johari, menyatakan bahwa tim telah
dikirim ke Australia untuk mempelajari teknik penangkapan dan pengelolaan buaya
(berita Anda). Dalam konteks global, Australia memang sering dianggap contoh
“best practice” dalam manajemen buaya. Sejak tahun 1970-an mereka memberlakukan
moratorium perburuan dan memperkuat regulasi kawasan habitat (Webb et al.,
2010). Salah satu strategi publik yang populer adalah program “Be Crocwise”,
yaitu kampanye edukasi publik agar orang memahami perilaku buaya dan cara
bertahan hidup di wilayah konflik (Webb et al., 2010).
Australia juga menerapkan relokasi buaya bermasalah ke
lokasi terkontrol, pengawasan sarang, serta sistem pemantauan kuantitatif yang
rutin (Webb et al., 2010). Jika Sarawak bisa mengadaptasi model ini secara
kontekstual, mungkin ada potensi mengurangi risiko tanpa merusak populasi buaya
sebagai unsur ekologi.
Namun, benar bahwa adaptasi tidak mungkin 1:1.
Infrastruktur, kapasitas personel, dana operasional, dan kondisi sosial-budaya
masyarakat lokal menjadi tantangan besar. Misalnya, mengelola santuari buaya
mungkin memerlukan akses jauh dari pemukiman, tetapi jika terlalu jauh, operasional
dan pengawasan menjadi rumit.
Tantangan Teknik & Ekologi
Memindahkan buaya, apalagi yang besar atau agresif, bukanlah
tugas ringan. Buaya memiliki wilayah teritorial, naluri bertahan, dan kemampuan
menemukan jalan kembali. Lokasi santuari yang salah bisa menciptakan kepadatan
tinggi atau persaingan sumber makanan, yang justru memicu konflik baru (The
Borneo Post, 2025).
Dari perspektif ekologi, buaya adalah predator puncak—mereka
mengendalikan populasi ikan, mamalia air, dan membantu menjaga keseimbangan
ekosistem sungai (Hassan et al., 2023; Webb et al., 2010). Jika populasi liar
dikurangi secara paksa tanpa strategi pemulihan yang hati-hati, bisa muncul
efek tak terduga pada ekosistem sungai dan pesisir.
Studi di Samarahan juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi
penangkapan atau relokasi buaya, tren kenaikan tetap terjadi—artinya upaya saat
ini belum cukup untuk membendung eskalasi (Hassan et al., 2023). Maka,
penanganan jangka panjang harus lebih dari sekadar “menangkap buaya yang
bermasalah”.
Hipotesis Interaksi Manusia–Buaya: Naluri vs Habitat
Dalam pernyataannya, Abang Johari menyebutkan bahwa ada
buaya yang tampak “agresif” dan ada yang tidak, bahkan di Australia mereka
hidup berdampingan dengan ternak kerbau tanpa konflik nyata. Ini menunjukkan
bahwa interaksi manusia–buaya bisa berbeda bergantung pada perilaku spesies dan
kondisi lingkungan.
Mungkin benar bahwa sebagian buaya bisa hidup toleran
terhadap bentuk tertentu interaksi manusia—sepanjang manusia tidak memicu
ancaman terhadap sarang atau wilayah teritorial. Tapi itu tidak berarti semua
buaya bisa “bersahabat”. Jadi, studi lebih rinci diperlukan: misalnya,
identifikasi buaya problematik (berulang menyerang) atau “non-problematic”,
pemetaan habitat aktif vs zona konflik, dan kajian genetik populasi.
Politik, Budaya, dan Respons Pemerintah
Secara politik, langkah mengirim tim ke Australia
menghadirkan citra responsif dari otoritas. Ini penting dalam membangun
kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius menghadapi risiko nyata. Ketika
Premier turun langsung ke lokasi kejadian dan menyampaikan simpati kepada
keluarga korban, dampaknya tak hanya simbolis, tetapi juga sebagai tekanan
moral untuk hasil konkret.
Namun, publik tentu mengharapkan lebih dari sekadar
retorika. Masyarakat pedesaan berharap kehadiran tim SFC di lapangan dalam
waktu cepat, peralatan deteksi jasad korban, dan tindakan pencegahan yang
proaktif. Abang Johari pun sempat memberi mandat bahwa dalam dua hari setelah
kejadian, operasi penginderaan jasad korban harus diambil alih oleh SFC dengan
peralatan mereka sendiri.
Kultur lokal juga penting: beberapa suku di Sarawak, seperti
Iban dan Melanau, menghormati buaya melalui mitos dan tabu tradisional.
Tindakan yang terlalu agresif terhadap buaya bisa berpotensi memicu resistensi
kultural dari masyarakat setempat (The Borneo Post, 2025).
Agenda Ke Depan: Strategi Holistik
Untuk meredam eskalasi konflik buaya di Sarawak, strategi
harus mencakup:
- Kajian
populasi dan pemetaan habitat secara periodik: Survei kuantitatif
(seperti metode spotting malam) harus dilakukan tiap tahun di
sungai-sungai rawan konflik. (Hassan et al., 2023)
- Edukasi
publik mirip “Be Crocwise”: agar warga memahami kapan dan di mana aman
berada dekat sungai, serta mengenali tanda bahaya.
- Zonasi
konflik & buffer zone: menetapkan zona aman di tepi sungai untuk
aktivitas manusia, menjauh dari habitat aktif buaya.
- Sistem
santuari/relokasi terkelola: zona konservasi khusus untuk buaya dari
area konflik, dengan pengawasan ilmiah dan operasional berkelanjutan.
- Regulasi
pengambilan hayati: dalam kondisi tertentu, pengaturan “take quota”
bisa dipertimbangkan agar konflik tidak terlalu merugikan manusia—tetapi
harus berdasarkan data dan evaluasi ilmiah.
- Kolaborasi
penelitian dan tukar pengalaman: belajar dari Australia, Papua Nugini,
atau negara lain yang sudah sukses mengelola konflik buaya (Webb et al.,
2010; Samuel et al., 2025).
- Pendekatan
budaya partisipatif: melibatkan komunitas lokal dalam pemantauan,
edukasi, dan pengambilan keputusan agar solusi diterima di akar rumput.
Harapan dari Air Berdenting
Krisis buaya di Sarawak bukanlah persoalan teknis semata,
melainkan persimpangan antara konservasi, kemanusiaan, dan politik. Mengirim
tim ke Australia adalah langkah awal yang penting—namun bukan jawaban tunggal.
Tantangan terbesarnya adalah merumuskan strategi berkelanjutan yang menghormati
keseimbangan ekosistem sekaligus melindungi keselamatan warga.
Jika model Australia bisa diadaptasi secara bijak, bukan
tidak mungkin Sungai-sungai di Sarawak kembali menjadi nadi kehidupan, bukan
deretan ancaman tersembunyi. Namun, hasil nyata baru akan terlihat ketika
kebijakan, budaya, dan sains berjalan bersama.