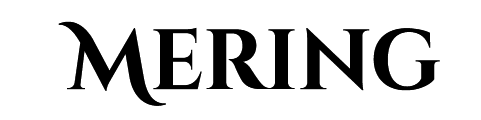|
| Tonton video launching buku Traveler Kampung |
Oleh Dessy Rizki
Bayangkan ini: seorang anak kampung dari perbatasan Indonesia–Malaysia, yang dulu mungkin lebih sering melihat babi hutan ketimbang kamera DSLR, tiba-tiba nyelonong masuk ke kota-kota megalopolis—New York, Tokyo, Washington DC—dan bukannya merasa “wah, keren”, justru merasa makin kampungan. Alexander Mering, penulis dua buku Traveler Kampung, bukanlah tipe turis Instagram yang berfoto dengan gaya yoga di tebing curam lalu kasih caption puitis hasil comot dari Pinterest. Ia lebih mirip orang kampung yang tersasar, lalu malah menuliskan kekampungan dirinya sebagai kaca pembesar untuk melihat dunia.Peluncuran bukunya kali ini, yang dilakukan secara online dari Yogyakarta, mungkin terlihat sederhana—hanya sebuah video yang diunggah ke kanal sosial medianya. Tapi justru di situ letak keasyikannya. Sebab Mering bukan sedang membangun panggung megah, melainkan sekadar menyatakan: “Nih, dua buku gue, sudah jadi, silakan dinikmati. Kalau nggak suka, ya tetaplah buku ini akan berdiri tegak, kayak bendera one pace di spion mobil Paspampres saat 17-an.”
Dua buku ini bukan fotokopi brosur wisata atau semacam katalog “tempat hits untuk healing”. Sampul warna sunset berisi 15 catatan perjalanan kampung ke kampung di Indonesia, sedang sampul biru menyimpan 10 catatan tentang kampung-kampung di luar negeri. Sebuah duet buku yang lahir dari catatan perjalanan panjang antara tahun 2005 hingga 2019—era ketika selfie masih pakai kamera digital, dan Wi-Fi gratis masih dianggap hadiah raja.
Mering menulis tidak dari menara gading, tapi dari jalanan kampung yang becek. Sebagian tulisan lahir ketika ia menjadi jurnalis, sebagian lagi dari pengalamannya sebagai communications specialist di Kantor Partnership for Governance Reform (Kemitraan) Jakarta. Nah, bagian ini agak absurd sekaligus brilian: karena bosan menulis laporan proyek yang kaku dan formal untuk donor, ia malah menulisnya seperti surat cinta. Bayangkan, para pembaca laporan yang biasanya ngantuk mendadak baper, padahal tanpa sadar mereka sedang membaca dokumen proyek. Kalau ada Nobel Sastra untuk laporan donor, mungkin Mering sudah angkat piala sambil senyum kecut.
Di balik kelucuannya, gaya menulis Mering punya daya pukau yang serius. Ia bisa menghadirkan tokoh, dialog, deskripsi, sampai pembaca merasa ikut duduk di bale-bale bambu, atau ikut tersesat di lorong kampung luar negeri. Ada kesederhanaan sekaligus kedalaman yang bikin cerita-cerita ini tetap asyik dan relevan.
Kenapa judulnya Traveler Kampung? Jawabannya sederhana tapi jleb: meski pernah tinggal di Jakarta hampir satu dekade, berkeliling separuh bumi, dan menapaki jalanan New York, Tokyo, hingga Los Angeles, Mering tetap merasa kampungan. “Saya merasa anak kampung paling kampungan ketika berada di kota besar,” katanya. Justru perasaan inilah yang membuat sudut pandangnya unik. Ia tidak menulis dari menara gedung pencakar langit, tapi dari mata seorang bocah kampung yang kebetulan bisa melihat dunia.
Motivasinya? Bukan mengejar MURI lagi (walau sudah pernah memecahkan rekor itu lewat buku 100 Anak Tambang Indonesia), bukan pula ingin pamer karya di galeri seni (meski bukunya The Shadow Knight sempat diluncurkan di Museum NuArt, Milik Nyoman Nuarta di Bandung). Motivasi utama Mering kali ini jauh lebih personal: mendokumentasikan pengalaman, mencatat kampung-kampung yang sering luput dari radar penulis perjalanan Indonesia era 2000-an, yang terlalu sibuk menulis soal menara Eiffel atau Disneyland, ketimbang menulis soal kampung halamannya sendiri.
Mering seakan ingin bilang: “Halo, kampung juga seksi, Bro. Jangan sampai kalah pamor dari kafe starbucks atau budapest.”
Buku biru bahkan membawa perspektif ini ke luar negeri. Ia menulis tentang orang-orang kampung di belahan dunia lain, tapi tetap dari kacamata seorang anak kampung. Di beberapa cerita, ia bahkan sengaja menempatkan dirinya yang kampungan sebagai tokoh, sehingga pembaca bisa ikut merasa canggung sekaligus terhibur.
Kini, di era ketika ponsel pintar sudah kawin resmi dengan kecerdasan buatan, buku Mering hadir bagai perlawanan kecil. Mirip fotografer yang tetap asyik motret dengan kameranya meski foto kini bisa dibuat dalam sekejap dengan AI image generator. Ada hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya digantikan algoritma. Seperti kata Yesus dari Nazaret ribuan tahun lalu: manusia hidup bukan dari roti saja. Lewat bukunya Mering menunjukkan bahwa hidup manusia tak cukup hanya dengan nonton konten TikTok doang.
Peluncuran online dari Yogyakarta ini mungkin terasa sangat sederhana. Tidak ada sorot lampu panggung, tidak ada MC dengan intonasi lebay, tidak ada “countdown” ala konser. Hanya sebuah video yang diberi sentuhan Ai menandai lahirnya dua buku. Simpel, kampungan, tapi tulus.
Dan di situlah justru daya reflektifnya: bahwa perjalanan sejati bukan sekadar menaklukkan destinasi, melainkan keberanian untuk mendokumentasikan hidup dengan cara yang jujur. Buku Traveler Kampung adalah cermin, bahwa jadi kampungan itu bukan aib, melainkan cara pandang. Kampung mengajari kita bagaimana merayakan detail, mendengarkan orang kecil, dan menertawakan diri sendiri.
Pada akhirnya, Mering seperti menanam papan kecil di tengah hiruk pikuk dunia digital: “Hei, masih ada ruang untuk cerita kampung. Masih ada tempat untuk ketulusan.” Dan siapa tahu, justru dari kampunglah kita bisa membaca dunia dengan lebih jernih, lebih kocak, dan masih manusiawi.
Jogja, 17 Agusutus 2025