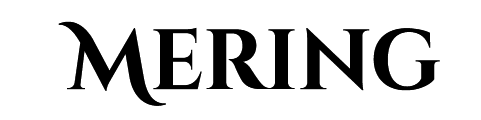Kabut tipis yang menyelimuti sebagian wilayah Kalimantan Barat bukan lagi sekadar fenomena musiman. Ia telah menjadi simbol dari krisis lingkungan yang kronis, yang tidak hanya mengaburkan langit biru, tetapi juga mencemari udara yang dihirup oleh jutaan manusia—terutama anak-anak yang belum mampu melindungi diri dari polusi yang membunuh perlahan. Kabut itu datang bukan dari langit, melainkan dari bumi yang terbakar. Hutan-hutan yang dahulu menjadi benteng alam kini luluh lantak oleh api, berubah menjadi abu karena kebutuhan ekspansi investasi—perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan tambang bauksit yang menjanjikan cuan instan tetapi menyisakan luka jangka panjang.
Situasi ini diungkap secara gamblang oleh Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo, yang sejak lama aktif mengawal isu-isu lingkungan di Kalbar. “Pohon-pohon yang biasanya menyaring udara dan menyerap karbon, kini telah ditebang dan dibakar. Akibatnya, tidak ada lagi penghalang bagi debu dan asap, sehingga manusia menjadi ‘penyerap’ polusi tersebut,” kata Agus dalam sebuah diskusi lingkungan yang digelar di Pontianak pekan lalu.
Kata-katanya bukan retorika. Ia berbicara dengan latar data yang telah dikumpulkan oleh berbagai organisasi, termasuk Yayasan Auriga yang mencatat lebih dari 1,25 juta hektare hutan di Kalbar hilang dalam dua dekade terakhir. Hilangnya hutan itu tidak hanya berarti kehilangan pohon dan satwa, tetapi juga melepaskan jutaan ton karbon ke udara, memperparah pemanasan global, dan mengubah hutan tropis menjadi zona bencana ekologis.
Sejak awal tahun 2000-an, laju deforestasi di Kalbar tak lagi terbendung. Ribuan hektare hutan primer—yang sebelumnya menjadi paru-paru dunia—berubah menjadi perkebunan sawit dalam waktu singkat. Ledakan permintaan pasar terhadap minyak sawit global dijawab dengan kemudahan izin, regulasi longgar, dan karpet merah bagi investor. Di atas kertas, ini menjadi narasi pembangunan yang menjanjikan. Tapi di balik angka investasi dan pertumbuhan ekonomi itu, terselip tragedi kemanusiaan: ribuan warga, termasuk anak-anak, jatuh sakit akibat kabut asap yang tidak pernah benar-benar hilang.
Menurut Society of Indonesia Science Journalists (SCISJ), dalam periode 2015 hingga 2020 saja, terdapat lebih dari 10.955 kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di Kalbar. Dari jumlah tersebut, anak balita menempati posisi kedua terbanyak dengan 1.238 kasus. Ini adalah angka yang menggambarkan dengan jelas siapa yang paling dirugikan dalam konflik laten antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Agus menegaskan bahwa kasus ISPA hanyalah gejala awal. “Anak-anak paling rentan karena sistem pernapasan mereka masih berkembang. Mereka juga belum punya kesadaran untuk mengenakan masker atau menjaga diri ketika kualitas udara memburuk. Akibatnya, mereka jadi korban paling awal dan paling berat,” jelasnya.
Ironisnya, meski dampaknya sangat terasa, banyak perusahaan diduga tetap menggunakan metode pembukaan lahan dengan cara membakar—karena jauh lebih murah dan cepat ketimbang menggunakan alat berat atau teknik ramah lingkungan lainnya. Ini adalah praktik yang dilarang secara hukum, namun faktanya terus berlangsung di lapangan. Pembakaran lahan menjadi modus klasik yang sukar diberantas karena lemahnya penegakan hukum, rendahnya pengawasan, dan sering kali ada pembiaran terselubung dari pihak berwenang.
Sementara itu, di tingkat kebijakan, pemerintah justru memberikan banyak kemudahan investasi dengan dalih membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Agus menyebut kondisi ini sebagai "investasi berkarpet merah", di mana hak-hak masyarakat menjadi korban pertama dari proyek-proyek ambisius yang tidak memperhitungkan dampak ekologisnya.
“Padahal masyarakat memiliki hak dasar atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman. Ketika investasi dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak warga, maka terjadilah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sejauh mana tanggung jawab negara—baik pemerintah pusat maupun daerah—terhadap anak-anak dan warga yang menjadi korban polusi dari kabut asap? Apakah nilai investasi yang masuk lebih penting daripada hak hidup sehat generasi penerus bangsa?
Hingga kini, belum banyak jawaban tegas. Pemerintah memang kerap menyampaikan rencana penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan), dari patroli udara, penyediaan teknologi modifikasi cuaca, hingga pendirian posko kesehatan. Tapi upaya-upaya itu bersifat reaktif, bukan preventif. Sumber masalahnya tetap dibiarkan: pembukaan lahan dengan api, lemahnya regulasi, dan ketidaktegasan hukum.
Sementara itu, masyarakat di lapangan terus menghirup udara bercampur racun. Anak-anak harus bersekolah dengan masker, balita dirawat di puskesmas karena batuk berkepanjangan, dan warga tua mengalami gangguan pernapasan kronis. Semua ini terjadi di tengah narasi besar bahwa Kalimantan adalah masa depan Indonesia, dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan megaproyek pembangunan yang mengelilinginya.
Agus pun mengingatkan bahwa jika akar persoalan tak diselesaikan, maka bencana ekologis ini hanya akan membesar. “Hutan bukan hanya sumber daya ekonomi, tapi juga benteng terakhir kesehatan kita. Jika hutan rusak, maka manusialah yang akan membayar harga termahalnya,” tegasnya.
Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya ada pada pemerintah. Perusahaan pemegang konsesi juga harus diberi sanksi tegas jika terbukti melakukan pembakaran atau pembiaran. Pemantauan berbasis satelit, penguatan peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan, serta peran aktif organisasi masyarakat sipil juga harus ditingkatkan.
Selain itu, aspek kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam agenda kebijakan daerah. Dinas Kesehatan harus bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, dan bahkan sektor pendidikan. Sekolah-sekolah harus dilengkapi dengan informasi kualitas udara harian, masker disediakan secara gratis, dan ruang ramah anak dibuat kedap udara saat terjadi kabut asap.
Pemerintah juga didorong untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan. Setiap keputusan investasi harus melewati uji dampak HAM dan lingkungan. Ketika masyarakat, terutama anak-anak, mulai menjadi korban dari keputusan politik dan ekonomi, maka pembangunan itu tak lagi bermakna. Sebab negara dibentuk bukan untuk memperkaya segelintir orang, tetapi untuk menjamin hak hidup warganya secara setara dan bermartabat.
Kalbar tidak sendiri dalam menghadapi krisis ini, tapi ia adalah contoh paling nyata bagaimana deforestasi yang terjadi secara sistematis dan dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang bisa menghancurkan tatanan sosial-ekologis yang telah diwariskan turun-temurun. Anak-anak yang hari ini batuk karena kabut asap bisa jadi kelak tumbuh dengan kapasitas paru-paru yang menurun, daya tahan tubuh melemah, dan risiko penyakit kronis lebih tinggi. Ini bukan prediksi, tetapi realitas yang sudah terjadi.
Dan ketika anak-anak yang sakit hari ini adalah generasi yang akan memimpin esok hari, maka kerusakan lingkungan bukan hanya ancaman ekologis—tetapi juga ancaman terhadap masa depan bangsa.