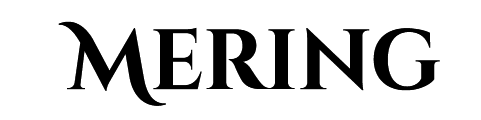Pontianak, 4 Mei 2025 – Di tengah gempuran kampanye
kesetaraan gender dan perlindungan hak anak yang gencar digaungkan dari kota
hingga ke pelosok desa, Kalimantan Barat justru menyuguhkan ironi yang
menyesakkan dada. Provinsi yang dikenal akan kekayaan budaya dan sumber daya
alamnya ini kini menanggung predikat kelam: sebagai wilayah dengan angka
perkawinan anak tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Barat, lebih dari 10.000 kasus perkawinan anak tercatat di provinsi ini. Sebuah angka yang tak hanya mengundang keprihatinan, tapi juga menjadi alarm keras akan krisis multidimensi yang tengah melanda generasi muda di Kalbar.
Di balik angka yang mencekam itu, tersembunyi ragam kisah dan alasan yang menyayat. Mulai dari tekanan budaya, keterbatasan ekonomi, hingga lemahnya sistem edukasi dan perlindungan anak. Semua saling terkait, membentuk pusaran persoalan yang tak mudah diurai.
Kabupaten Ketapang: Titik Merah di Peta Perkawinan Anak
Jika harus menunjuk satu wilayah sebagai episentrum dari
persoalan ini, maka Kabupaten Ketapang menempati posisi paling atas. Dari
catatan DP3A Kalbar, Ketapang menyumbang sekitar 2.000 kasus—tertinggi
dibanding kabupaten lain. Disusul Landak dengan 1.400 kasus, Sintang 1.100
kasus, dan Sambas 1.000 kasus.
“Ini bukan hanya sekadar angka, ini adalah anak-anak yang kehilangan masa depannya terlalu dini,” ungkap Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Niyah Nurniyati, saat diwawancarai di Pontianak, Sabtu (3/5/2025).
Menurut Niyah, tren ini menunjukkan perlunya pendekatan baru, tak cukup hanya dengan peraturan formal semata. Harus ada terobosan dari lembaga-lembaga kunci seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan ruang edukasi dan refleksi bagi calon pengantin usia dini.
Inspirasi dari Cilegon: Konseling Sebelum Akad
Niyah pun menyinggung contoh baik yang bisa diadaptasi oleh
Kalbar: sebuah program preventif yang telah dijalankan di Pengadilan Agama
Cilegon, Banten. Di sana, setiap anak yang mengajukan dispensasi nikah
diwajibkan menjalani sesi konseling terlebih dahulu.
“Mereka punya ruang khusus, semacam ruang konseling. Di situ anak-anak diberi nasehat, pencerahan, edukasi tentang pernikahan dan tanggung jawabnya. Hasilnya banyak yang akhirnya mundur, batal menikah,” ujar Niyah dengan nada optimistis.
Menurutnya, pendekatan ini bukan untuk menghalangi hak anak dalam memilih jalan hidupnya, tapi justru untuk membantu mereka memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil di usia yang belum matang secara psikologis maupun emosional.
“Kalau cuma dinasehati orang tua mungkin tidak digubris, tapi kalau masuk ke ranah hukum, ada konselor, psikolog, mungkin mereka lebih mikir lagi,” tambahnya.
Faktor Budaya dan Geografis Jadi Pemicu
Namun, tak semua kasus bisa diselesaikan hanya dengan
edukasi formal. Kalimantan Barat adalah provinsi yang luas, dengan keragaman
etnis, budaya, dan kondisi geografis yang unik. Di beberapa wilayah seperti
Sambas, kedekatan dengan negara tetangga Malaysia justru menjadi penyulut lain
dalam praktik perkawinan anak.
“Banyak anak SD atau anak-anak yang putus sekolah, tidak punya pilihan hidup selain bekerja ke Malaysia. Di sana, mereka bertemu jodoh di tempat kerja, dan akhirnya pulang kampung untuk menikah. Usianya belum 19 tahun,” jelas Niyah.
Fenomena ini membuka tabir persoalan lain yang tak kalah krusial: migrasi anak usia sekolah ke luar negeri untuk bekerja. Situasi ini sangat rentan terhadap eksploitasi, kehilangan akses pendidikan, dan tentu saja menjurus pada keputusan menikah muda.
Peran Orang Tua dan Masyarakat yang Belum Optimal
Salah satu akar dari persoalan ini adalah lemahnya pemahaman
orang tua tentang pentingnya perlindungan anak dan pendidikan yang
berkelanjutan. Dalam banyak kasus, justru orang tua menjadi aktor utama yang
mendorong anaknya untuk menikah dini.
Ada beberapa motif: takut anak hamil di luar nikah, ingin meringankan beban ekonomi, atau sekadar karena “ikut-ikutan tetangga”. Dalam masyarakat yang masih memegang erat budaya patriarki, anak perempuan khususnya dianggap lebih baik "diserahkan" pada suami saat mulai remaja.
“Orang tua harusnya menjadi garda terdepan perlindungan anak. Tapi di banyak kasus, mereka justru mendorong. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tegas Niyah.
Regulasi Ada, Tapi Lemah di Implementasi
Sebenarnya, secara nasional Indonesia sudah mengatur batas
minimal usia menikah di angka 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan,
sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan. Namun, aturan ini bisa dilonggarkan melalui dispensasi pengadilan.
Celakanya, di banyak daerah dispensasi ini diberikan dengan cukup mudah, bahkan tanpa kajian psikologis atau konseling yang memadai. Maka, tak mengherankan jika banyak anak di bawah umur tetap bisa menikah secara sah secara hukum, meski bertentangan dengan semangat perlindungan anak.
Solusi Harus Menyentuh Akar: Pendidikan Seksual dan Keterampilan Hidup
Berbicara tentang solusi, Niyah Nurniyati menekankan
pentingnya pendekatan multidimensi. Tidak cukup hanya dari sisi hukum, tapi
juga melalui jalur pendidikan dan penguatan peran komunitas.
“Anak-anak perlu dibekali pendidikan kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, dan pemahaman tentang relasi yang sehat. Jangan sampai mereka berpikir bahwa menikah adalah satu-satunya cara untuk ‘selamat’,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar sekolah-sekolah mulai membuka ruang diskusi yang sehat tentang kehidupan dewasa, risiko pernikahan dini, dan pentingnya masa remaja sebagai fase pembentukan karakter.
“Kalau kita tidak beri ruang bicara, mereka akan cari tahu sendiri di internet. Dan itu justru bahaya kalau sumbernya tidak kredibel,” tambahnya.
Keterlibatan Lintas Sektor Jadi Kunci
Di tengah tantangan yang kompleks ini, solusi tidak bisa
berjalan sendiri-sendiri. KPAD, DP3A, Kemenag, Pengadilan Agama, LSM, dan tentu
saja masyarakat harus duduk bersama merumuskan langkah konkret.
Program seperti “Sekolah Orang Tua”, pelatihan keterampilan remaja, kampanye media sosial tentang bahaya nikah muda, hingga penyediaan ruang konseling gratis bagi calon pengantin muda bisa menjadi langkah awal.
Juga perlu ada penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama agar bisa menjadi agen perubahan di masyarakat. Di banyak wilayah, tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan keluarga.
Harapan Masih Ada, Jika Kita Mau Bergerak
Meski situasi di Kalimantan Barat tergolong darurat, harapan
belum sirna. Keberhasilan program konseling di Cilegon, serta
inisiatif-inisiatif lokal yang mulai bermunculan di beberapa daerah Kalbar
menjadi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah.
Yang dibutuhkan adalah keseriusan semua pihak untuk mengakui bahwa perkawinan anak bukan sekadar persoalan adat atau pilihan individu. Ini adalah krisis yang bisa menggerogoti masa depan generasi bangsa, jika tidak segera ditangani.
Karena di balik setiap pernikahan dini, ada satu masa depan anak yang terenggut. Ada mimpi yang tertunda. Dan ada potensi yang gagal tumbuh karena kita lalai memberikan perlindungan.
Catatan Redaksi:
Jika Anda mengenal anak yang berada dalam situasi rentan atau membutuhkan bantuan hukum dan konseling terkait perkawinan anak, silakan hubungi layanan pengaduan KPAD terdekat atau lembaga perlindungan anak resmi di wilayah Anda.