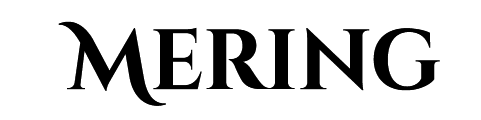|
| Ilustrasi AI |
Pontianak, 17 Januari 2026 – Kasus penyerangan terhadap
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh warga negara asing (WNA) asal
China di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, terus menjadi sorotan publik.
Polda Kalimantan Barat (Kalbar) baru saja mengirimkan surat resmi ke Kedutaan
Besar (Kedubes) China di Jakarta untuk memberitahukan proses hukum yang sedang
berjalan terhadap dua tersangka WN China. Insiden yang terjadi pada Desember
2025 lalu ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran soal keamanan di area
pertambangan, tapi juga menyentuh isu diplomasi antara Indonesia dan China.
Bagaimana kronologi kejadian ini, dan apa implikasinya bagi hubungan bilateral
kedua negara?
Insiden bermula dari kegaduhan di kawasan pertambangan emas
milik PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten
Ketapang. Pada 14 Desember 2025, sekelompok WN China diduga terlibat bentrokan
dengan petugas keamanan sipil dan anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya
Digdaya (Yonzipur 6/SD). Menurut laporan awal, keributan dipicu oleh
perselisihan internal di antara pekerja tambang, yang kemudian meluas menjadi
penyerangan fisik. Satu petugas pengamanan sipil dan lima prajurit TNI menjadi
korban, dengan luka-luka akibat senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalbar,
Kombes Pol Raswin Bachtiar Sirait, menjelaskan bahwa dua WN China berinisial WL
dan WS telah ditetapkan sebagai tersangka utama. "Masih berproses atau
berjalan penyidikannya. Pemberitahuan ke kedutaan juga sudah," ujar Raswin
saat dikonfirmasi media pada 14 Januari 2026. Keduanya ditangkap karena membawa
senjata tajam seperti pisau dan parang tanpa izin sah, yang digunakan dalam
insiden tersebut. Saat ini, WL dan WS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)
Polda Kalbar, sementara penyidik mempersiapkan pelimpahan berkas ke Kejaksaan.
"Ya secepatnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum apabila sudah lengkap
semuanya," tambah Raswin.
Penetapan tersangka ini didasarkan pada Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang melarang
kepemilikan, pembawaan, atau penggunaan senjata tajam tanpa hak. Hukum ini,
yang lahir dari kondisi darurat pasca-kemerdekaan, menetapkan ancaman pidana
maksimal 10 tahun penjara bagi pelanggar. Aturan ini berlaku ketat untuk
senjata seperti celurit, pisau, atau parang yang dibawa di tempat umum tanpa
alasan yang dibenarkan, seperti untuk keperluan pertanian atau pekerjaan rumah
tangga. Dalam konteks insiden Ketapang, penggunaan senjata tajam di area
pertambangan dianggap sebagai pelanggaran berat karena berpotensi mengancam
keselamatan umum.
Latar belakang insiden ini tak lepas dari dinamika
pertambangan emas di Ketapang, yang dikenal sebagai salah satu wilayah kaya
mineral di Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang memiliki cadangan emas
signifikan, dengan aktivitas penambangan yang sering kali melibatkan investor
asing, termasuk dari China. PT SRM, perusahaan yang menjadi lokasi kejadian,
memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk operasi produksi emas sejak 2018
hingga 2030. Berlokasi di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, perusahaan ini
menggarap area dengan potensi ekonomi tinggi. Namun, operasinya tak luput dari
kontroversi. Direktur PT SRM, Li Changjin, sempat mempertanyakan kehadiran TNI
di lokasi tambang, menyebut area tersebut masih dalam status sengketa hukum.
Menurut catatan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM), pertambangan emas di Ketapang sering diwarnai aktivitas
ilegal. Pada 2024 saja, kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai lebih
dari Rp1 triliun, dengan ribuan meter kubik batuan bijih emas yang
dieksploitasi tanpa izin. Banyak kasus melibatkan WN China, seperti deportasi
tiga WNA pada akhir 2025 karena terlibat aktivitas ilegal di tambang serupa.
Insiden di PT SRM diduga bermula dari konflik internal, di mana 15 WN China awalnya
membuat keributan, merusak kendaraan perusahaan, dan kemudian bentrok dengan
petugas. Total, 29 WN China diamankan oleh Imigrasi Ketapang, dengan 27 di
antaranya dideportasi kembali ke negara asal, sementara dua lainnya—WL dan
WS—menghadapi proses pidana.
Pengiriman surat oleh Polda Kalbar ke Kedubes China
merupakan langkah protokoler standar dalam kasus yang melibatkan warga negara
asing. Surat tersebut bertujuan memberi tahu pemerintah China tentang status
hukum warganya, memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama proses, seperti
akses konsuler. Hal ini sejalan dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler
1963, yang diikuti kedua negara. Namun, kasus ini juga menyoroti ketegangan
potensial dalam hubungan Indonesia-China, terutama terkait tenaga kerja asing
(TKA).
Hubungan diplomatik Indonesia dan China telah berlangsung
sejak 1950, menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang mengakui
Republik Rakyat China. Meski sempat beku pada 1965 akibat dinamika politik
dalam negeri, hubungan normal kembali pada 1990. Di era Presiden Joko Widodo
dan Xi Jinping, kerjasama bilateral semakin erat, terutama di bidang ekonomi.
China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, dengan investasi mencapai
miliaran dolar di infrastruktur dan pertambangan. Proyek seperti Jalur Sutra Maritim
dan Poros Maritim Global memperkuat ikatan ini, termasuk peningkatan pertukaran
budaya dan pariwisata.
Namun, isu TKA China sering menjadi perdebatan. Kebijakan
bebas visa kunjungan sejak 2015 memudahkan masuknya warga China, tapi kerap
disalahgunakan untuk bekerja ilegal. Kasus di Ketapang bukan yang pertama;
sebelumnya, deportasi massal WN China terjadi di berbagai tambang ilegal di
Kalbar. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengawasan, sementara China
mendorong perlindungan warganya. Dalam pertemuan bilateral terbaru, Menteri
Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa China tetap mitra penting, tapi
aturan hukum domestik harus dihormati.
Implikasi dari kasus ini lebih luas daripada sekadar pidana.
Ia menekankan perlunya regulasi ketat di sektor pertambangan untuk mencegah
konflik serupa. Pemerintah daerah Kalbar telah meningkatkan pengawasan,
bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan. Di sisi lain, kasus
ini bisa menjadi pelajaran bagi investor asing untuk mematuhi norma lokal,
termasuk penggunaan tenaga kerja Indonesia secara proporsional.
Sementara proses hukum berlanjut, masyarakat Ketapang
berharap insiden ini tak mengganggu aktivitas ekonomi. Pertambangan emas
menyumbang lapangan kerja bagi ribuan warga lokal, tapi juga berisiko merusak
lingkungan jika tak dikelola baik. Vonis bebas atau ringan dalam kasus tambang
ilegal sebelumnya, seperti yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Pontianak pada
2025, menunjukkan tantangan penegakan hukum.
Polda Kalbar menjanjikan transparansi dalam penanganan,
dengan pelimpahan ke jaksa dalam waktu dekat. Bagi WL dan WS, ancaman 10 tahun
penjara menjadi pengingat bahwa hukum Indonesia berlaku adil bagi siapa pun,
termasuk warga asing. Kasus ini juga mengingatkan kita pada pentingnya
diplomasi yang matang untuk menjaga hubungan Indonesia-China tetap harmonis di
tengah dinamika global.
Dalam konteks lebih besar, hubungan bilateral kedua negara
terus berkembang. Pada 2025, peringatan 75 tahun diplomasi ditandai dengan
komitmen baru di bidang investasi dan pertukaran masyarakat. KBRI Beijing
bahkan mendorong "persahabatan lampaui formalitas" untuk memperkuat
ikatan sosial. Namun, kasus seperti di Ketapang menekankan perlunya
keseimbangan antara kerjasama ekonomi dan penegakan kedaulatan hukum.
Akhirnya, insiden ini menjadi cermin bagi pemerintah untuk
memperketat pengawasan TKA, memastikan bahwa investasi asing membawa manfaat
tanpa menimbulkan konflik. Masyarakat Indonesia berharap proses hukum berjalan
lancar, sambil menjaga stabilitas di wilayah perbatasan seperti Kalbar. Dengan
pendekatan yang bijak, kasus ini bisa menjadi momentum positif untuk memperkuat
kerjasama, bukan sebaliknya.